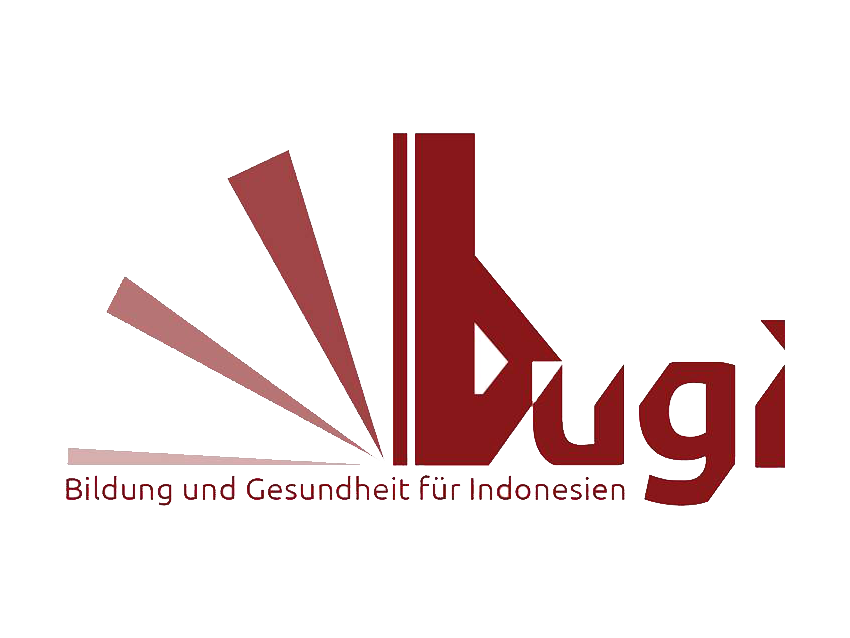Oleh Jannah Maryam Ramadhani, S.Psi
Penulis buku „Menikah“, saat ini menempuh program Master Psikologi Sosial di Universitas Indonesia
Kita tentu pernah tau kalimat pengharapan yang berbunyi, “Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper”. Setiap manusia berlomba-lomba untuk mencapainya. Maka tidak heran jika semakin banyak pusat-pusat kebugaran didirikan baik itu dalam bentuk fitness atau gym center, studio yoga, zumba, bahkan Muay Thai. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi sosial media sekarang ini seperti facebook dan twitter membuat banyak orang lebih gampang mengakses berbagai informasi seputar kesehatan tentang gizi makanan, diet, dan mencegah berbagai penyakit. Hal yang menggembirakan ini sejalan dengan program-program pemerintah Indonesia yang terus gencar berusaha memberi peluang terhadap akses kesehatan dan pendidikan terhadap warga negaranya melalui pengadaan rumah sakit, puskesmas, layanan BPJS, dan beasiswa pendidikan. Meskipun tidak bisa dipungkiri dari sekitar 200 juta lebih penduduk Indonesia yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2014 ada sekitar 28,28 juta orang masih dikategorikan penduduk miskin. Tolok ukur yang dilakukan BPS untuk menjangkau kriteria miskin itu sendiri didasari oleh ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Seseorang dikatakan miskin bila rata-rata pengeluaran perkapita perbulan lebih kecil dari nilai garis kemiskinan (GK).
Dengan beragamnya persoalan yang harus ditangani oleh Pemerintah Indonesia terhadap 200 juta lebih kepala, dimana dalam setiap kepala ada jutaan kemauan, jutaan gagasan, jutaan penyakit, dan ada jutaan kelamin, tentu sudah dipastikan ada yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Sebagai penulis yang erat berkegiatan dalam isu-isu keragaman gender dan seksualitas, saya hendak mengetengahkan bahwa kita masih jauh tertinggal dengan negara-negara maju dalam menyikapi keragaman gender dan seksualitas disamping persoalan ekonomi dan perpolitikan yang kian carut-marut dengan isu-isu korupsinya. Karena ketika kita membicarakan tubuh yang kuat dan jiwa yang sehat ada pertimbangan psikologis dan mental yang erat kaitannya terhadap gender dan seksualitas individu.
Sedari kanak-kanak kita telah diperkenalkan dengan apa itu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, memaknai diri menjadi laki-laki dan perempuan itu tidaklah sesederhana yang kita pikirkan selama ini. Karena ada perluasan pengertian terhadap gender dan seksualitas. Ilmu Psikologi modern (Diamond, 2000) banyak melahirkan istilah seperti transseksualisme, transgenderisme, interseks, autogynephilia, fetisisme, dan lain sebagainya. Setiap dari istilah itu mengarah pada persoalan gender individu yang belum tentu bisa dikategorikan homoseksual. Asosiasi Psikologi Amerika (APA) telah menerangkan bahwa antara identitas gender individu dan orientasi seksual itu berbeda pengertian, meskipun saling berkaitan.
Di tengah ratusan juta warga negara Indonesia, persoalan gender dan seksualitas ini tentu sangatlah penting. Karena ketika salah penamaan kondisi gender individu, maka salah jugalah perlakuan terhadapnya. Dalam perspektif kesehatan bisa disebut malpraktik. Sama halnya ketika seseorang dianggap sakti karena sering kesurupan dan berbicara dengan jin, padahal ketika ditelusuri secara ilmiah ternyata bagian dari gejala Schizophrenia. Kecenderungan salah persepsi juga dialami oleh transgender yang dianggap sebagai homoseksual. Padahal homoseksual sendiri merupakan bagian dari orientasi seksual yang juga bukan merupakan gangguan kelainan jiwa sebagaimana Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) dan Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) telah terbitkan sebagai acuan bagi para Psikolog, ilmuwan Psikologi, dan Psikiater.
Sebenarnya bukan keterbatasan pemahaman tentang gender dan seksualitas saja yang menjadi permasalahan, melainkan profesionalitas seorang Psikolog, ilmuwan Psikologi atau Psikater terkadang berbenturan dengan nilai-nilai personalnya menyikapi keberagaman gender dan seksualitas. Tidak sedikit di antara praktisi Psikologi, ilmuwan Psikologi, atau Psikater yang menjustifikasi seorang homoseksual sebagai bentuk kelainan jiwa atau menganggap transgender bagian dari perilaku yang menular. Hal ini tentu saja mengabaikan pedoman ilmiah yang telah dimaktubkan. Maka tidak heran di Indonesia banyak gay atau lesbian berusaha menyangkal orientasi seksualnya (denial), lalu kemudian memilih menikah secara heteroseksual, meskipun diam-diam melakukan hubungan seksual sejenis di luar dari pernikahan heteroseksual tersebut. Sedangkan para transgender lebih memilih pengobatan instan seperti suntik silikon atau suntik hormon tanpa preskripsi dari dokter yang kompeten, karena dianggap sebagai solusi yang memadai. Bagi gay dan lesbian yang melakukan pernikahan heteroseksual tersebut tentu berisiko tinggi terhadap penyakit menular seksual ketika ditambah keterbatasan pengetahuan tentang HIV/AIDS. Begitu pula transgender yang tidak sedikit meregang nyawa akibat salah suntik silikon.
Menurut tim estimasi Menteri Kesehatan tahun 2010 (dalam paramaters of social exlusion of waria PNPM Peduli, 2014) ada sekitar 30.348 transgender di Indonesia dan laporan dari United Nations (UN) “Being LGBT in Asia” (2014) nyaris mendekati seratus persen Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) pernah menjadi korban tindak kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal. LGBT itu ada di setiap belahan dunia dan berasal dari ragam usia, ragam agama, dan etnis. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa keberagaman gender dan seksualitas itu menjadi salah satu isu yang krusial untuk ditangani.
Dalam hal ini saya tidak sedang menggaungkan agar pernikahan sejenis dilegalkan secepatnya sebagaimana Amerika Serikat telah laksanakan secara nasional di bulan Juni lalu (The New York Times, 2015), karena dalam lembaga pernikahan, isu pernikahan usia muda dan pernikahan beda agama masih menjadi polemik yang harus diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan pernikahan sejenis.
Sebagaimana UU Perkawinan 1974 di Indonesia masih mengatur batas minimal pernikahan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Yayasan Kesehatan Perempuan (BBC, 2014) meneliti bahwa usia muda tersebut riskan bagi kesehatan reproduksi perempuan sekaligus berdampak pada kemiskinan. Menurut saya sebagai penulis, usia 16 tahun itu seharusnya diberdayakan dalam aspek pendidikan dan ketrampilan agar mandiri secara ekonomi dan matang secara emosional terlebih dahulu dibandingkan menikah. Maka tidak mengherankan data tingkat perceraian di Indonesia yang diungkapkan oleh Kementerian Agama (Republika, 2014) juga meningkat dari tahun ke tahun.
Tingginya disparitas status kesehatan antara penduduk yang miskin dan kaya; heteroseksual dan homoseksual; perempuan dan laki-laki tersebut idealnya bisa dijembatani melalui efektivitas program inklusi sosial yang disokong optimal oleh pemerintah. The Yogyakarta Principles ( 2007) dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama memenuhi standar kesehatan mental dan fisik tanpa diskriminasi yang berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Kesehatan tubuh dan reproduksi merupakan aspek fundamental yang harus dipenuhi. Akan tetapi, pada prakteknya di lapangan tidak semudah apa yang telah dimuat secara resmi dalam prinsip-prinsip Yogyakarta tersebut.
Sebuah studi yang dilakukan oleh The Williams Institute, Universitas California, Los Angeles (2014) mengemukakan bahwa inklusi sosial yang melibatkan LGBT berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi. Dalam hal ini, ketika individu LGBT mendapatkan haknya mengembangkan potensi terbaik melalui pendidikan, pelatihan, dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi membuka peluang lebih luas untuk menaikkan pendapatan dan investasi, dikarenakan lebih fokus pada pengaktualisasian diri dalam lingkungan sosial dan pekerjaan dibandingkan jika ditindas dan dikucilkan dalam masyarakat.
Fenomena yang terjadi di Indonesia kerap kali bertolak belakang dari hasil studi tersebut dimana banyak ditemui transgender yang putus sekolah dan diusir keluarga karena dianggap aib. Atau kasus depresi yang berkepanjangan pada gay dan lesbian karena ketakutan dalam memendam orientasi seksualnya. Menjadi LGBT cenderung dikonotasikan sebagai penyebab HIV/AIDS, padahal merujuk pada pernyataan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (Tempo, 2015) perempuan berjilbab dan ibu rumah tangga pun banyak terkena HIV/AIDS. Sehingga terpatahkan anggapan yang mengatakan bahwa HIV/AIDS sebagai penyakit para LGBT dan perempuan nakal. Karena intinya setiap orang berpotensi untuk terkena HIV/AIDS sama halnya mengidap kanker atau tumor. Hal yang perlu diperhatikan seharusnya kesadaran akan perlakuan seksual secara aman dan bertanggung jawab, salah satunya melalui penggunaan kondom sebagai antisipasi dini. Walaupun pada beberapa kebijakan daerah seperti wacana pembatasan penjualan kondom di Bengkulu (Kompas, 2015) dianggap sebagai solusi untuk mencegah penularan HIV/AIDS merupakan sebuah kesalahan fatal menurut saya. Membatasi penjualan kondom bukan alasan yang tepat, akan tetapi melalui pendidikan seksual yang diajarkan sejak remaja membuat setiap orang lebih sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan bertanggung jawab.
Demi mengantisipasi kerancuan dalam menangani persoalan gender dan seksualitas maka penting kiranya di Indonesia didirikan semacam pusat gender dan seksualitas yang kompeten di bidangnya. Di beberapa negara maju di Eropa dan Amerika telah banyak tenaga profesional yang kompeten menangani persoalan tersebut. Sehingga setiap persoalan yang berkaitan dengan seksualitas dapat ditangani secara profesional demi kehidupan masyarakat yang sejahtera, sehat secara ragawi dan rohani.
Daftar Pustaka
American Psychological Association. (http://www/apa/org/topics/lgbt/transgender.aspx diakses Juni 2015)
Badan Pusat Statistik. 2014. (http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488 diakses Juni 2015)
Badgett, M.V. Lee, et al. 2014. The relationship between LGBT inclusion and economic development: An analysis of emerging economies. Los Angeles, California: The Williams Institute.
BBC. 2014. MK tolak naikkan batas usia minimal untuk menikah. (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618_indonesia _mk_nikah diakses Juni 2015)
BBC. 2015. MK tolak uji materi soal nikah beda agama. (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618_indonesia_mk_nikah_bedaagama diakses Juni 2015)
BBC. 2015. Batas usia pernikahan dini digugat. (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141218_pernikahandini diakses Juni 2015)
Diamond, Milton. 2000. Sex and Gender: Same or Different?, Feminism & Psychology, Vol. 10, No. 1, 46 – 54.
Kompas. 2015. Cegah HIV dengan Pembatasan Kondom, DPRD Bengkulu Dikritik. (http://regional.kompas.com/read/2015/06/20/03262761/Cegah.HIV.dengan.Pe mbatasan.Kondom.DPRD.Bengkulu.Dikritik diakses Juni 2015)
Maslim, Rusdi. 2002. Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III. Jakarta
Parameters of Social Exlusion of Waria PNPM Peduli, May 2014.
Republika. 2014. Tingkat Perceraian Indonesia Meningkat Setiap Tahun, ini Datanya. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkatperceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya diakses Juni 2015)
The New York Times. 2015. Supreme Court Ruling Makes Same-Sex Marriage a Right Nationwide. (http://www.nytimes.com/2015/06/27/us/supreme-court-samesex-marriage.html?_r=0 diakses Juni 2015)
Tempo. 2015. Ratusan Hijaber Terinfeksi HIV/AIDS, ini penyebabnya. (http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/08/058672908/ratusan-hijaberterinfeksi-hiv-aids-ini-penyebabnya diakses Juni 2015)
UNDP, USAID. 2014. Being LGBT in Asia: Indonesia Country Report. Bangkok. (http://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/publication/Being_LGBT_in_A sia_Indonesia_Country_report_2014.pdf Diakses Juni 2015)
Yogyakarta Principles. 2007. Yogyakarta Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity. (www. yogyakartaprinciples.org diakses Juni 2015)